Setiap kali banjir melanda Jakarta, orang selalu menghubungkannya dengan Sungai Ciliwung dan anak-anak sungainya. Sungai-sungai di Jakarta memang sudah dianggap merupakan tempat pembuangan sampah yang paling murah. Tanpa peduli dampaknya, pembuangan sampah terus saja terjadi, meskipun pada 2002 lalu Jakarta pernah mengalami pula banjir hebat.
Namun berbeda dengan keadaan pada masa kini, pada masa lampau Ciliwung merupakan sumber kehidupan utama masyarakat karena berbagai aktivitas dilakukan di sini. Mulai dari keperluan rumah tangga sehari-hari hingga jalur perdagangan internasional. Ciliwung mulai berperan sejak zaman purba, ketika manusia prasejarah menghuni Jakarta.
Puncaknya, pada abad ke-15 dan ke-16 pelabuhan Sunda Kelapa di muara Ciliwung, telah dikenal luas oleh pedagang-pedagang seantero Nusantara dan internasional. Orang-orang Belanda yang datang paling awal antara lain menulis, “Kota ini dibangun seperti kebanyakan kota-kota di Pulau Jawa. Sebuah sungai indah, berair jernih dan bersih, mengalir di tengah kota” (Hikayat Jakarta, 1988). Itulah Ciliwung pada awalnya.
Pelabuhan Sunda Kelapa dikatakan ramai didatangi pedagang, meskipun terbujur sepanjang satu atau dua kilometer di atas potongan-potongan tanah sempit. Namun setelah dibersihkan, Ciliwung menjadi lebar. Hal ini memungkinkan sepuluh buah kapal dagang dengan kapasitas sampai 100 ton, masuk dan berlabuh dengan aman di Sunda Kelapa.
Menurut arsip sejarah lain, air Ciliwung waktu itu mengalir bebas, tidak berlumpur, dan tenang. Meskipun gempa-gempa besar sempat mengacaukan aliran pembuangan air, Ciliwung tidak seberapa tercemar. Karena itu banyak kapten kapal masih singgah untuk mengambil air segar yang cukup baik, untuk diisikan ke dalam botol-botol dan guci-guci mereka.
Sejak kedatangan bangsa Belanda, maka Batavia (nama pengganti Sunda Kelapa) dibangun seperti tata letak kota-kota di Belanda, yakni berupa tembok kota, parit, dan berderet-deret rumah. Dengan demikian, menurut Jean-Baptiste Tavernier sebagaimana dikutip van Gorkom, Ciliwung memiliki air yang paling bersih dan paling baik di dunia (Persekutuan Aneh, 1988).
Tidak berlebihan kalau ketika itu Batavia mendapat julukan “Ratu dari Timur”. Banyak orang asing yang datang, tak segan-segan memberikan sanjungan yang tinggi kepada Batavia. Bahkan menyamakannya dengan negara-negara di Eropa.
Pada saat dibangun Belanda, kota Batavia berbentuk bujur sangkar dengan panjang kira-kira 2.250 meter dan lebar 1.500 meter. Kota ini terbelah oleh Ciliwung menjadi dua bagian yang hampir sama besar. Masing-masing bagian dipotong lagi oleh parit-parit yang saling sejajar dan saling simpang. Sejumlah jalan juga dibangun sehingga penampang kota berpola kisi-kisi. Pola seperti inilah yang dipandang mampu melawan amukan air di kala laut pasang dan banjir di dalam kota karena air akan saling berpencar ke segala penjuru. Saat ini kota tersebut berada di wilayah Kota Tua Jakarta.
Bencana Ekologi
Tidak disangka-sangka, pada 1699 Gunung Salak di Jawa Barat meletus. Erupsinya sungguh berdampak besar. Karena itu iklim Batavia menjadi buruk, kabut menggelantung rendah dan beracun, parit-parit tercemar, dan penyakit-penyakit aneh bermunculan. Batavia pun berganti julukan menjadi “Kuburan dari Timur”, bukan lagi “Ratu dari Timur”. Sejak itu, Ciliwung mulai kotor.
Seperti halnya pemerintahan zaman sekarang, dulu pun banyak pihak saling tuding terhadap bencana ekologi tersebut. Mereka bukannya memasalahkan kebijakan Kompeni atau VOC sendiri, tetapi justru cenderung menuding pendahulu-pendahulunya. Mereka dinilai salah karena telah membangun kota dengan menyontoh kota gaya Belanda. “Batavia adalah kota bercorak tropis. Berbeda jauh dengan Belanda yang memiliki empat musim,” begitu kira-kira kata para penentang.
Sebagian lagi menduga, bencana ekologi itu disebabkan oleh kepadatan penduduk. Batavia memang semula dirancang sebagai kota dagang. Karenanya, banyak pendatang kemudian menetap secara permanen di sini. Sebagai kota dagang, tentu Batavia mempunyai magnet kuat.
Segera, lingkungan alam Batavia mengalami perubahan fundamental setelah berbagai daerah di sekitarnya dibersihkan dari hutan-hutannya untuk membudidayakan tanaman tebu. Ternyata, budi daya itu juga mencemari air dan menanduskan tanah. Apalagi berbagai pabrik gula sangat membutuhkan kayu bakar yang demikian banyak jumlahnya. Karena terletak di dekat sungai, maka pabrik-pabrik gula itu ikut menyokong pencemaran air bersih di Batavia, sekaligus mengurangi daerah resapan air.
Dalam penelitian tahun 1701 terungkap bahwa daerah hulu Ciliwung sampai hilir di tanah perkebunan gula telah bersih ditebangi. Sebagai daerah yang terletak di tepi laut, tentu saja Batavia sering kali kena getahnya. Kalau sekarang Jakarta hampir selalu mendapat “banjir kiriman” dari Bogor, dulu “lumpur kiriman” dari Cirebon bertimbun di parit-parit kota Batavia setiap tahunnya.
Pada awal abad ke-19 Batavia tidak lagi merupakan benteng kuat dan kota berdinding tembok. Karenanya, pada awal abad ke-20 Batavia sudah menjadi kota yang berkembang dengan penduduk berjumlah 100.000 orang. Bahkan dalam beberapa tahun saja penduduk kota sudah meningkat menjadi 500.000 orang. Adanya nama-nama tempat yang berawalan hutan, kebon, dan rawa setidaknya menunjukkan dulu Jakarta merupakan kawasan terbuka. Sayang, kini sudah berubah menjadi kawasan tertutup (tempat hunian).
Begitu pula adanya wilayah yang berawalan kampung. Dulu istilah kampung mengacu pada sederetan daerah permukiman orang-orang pribumi yang terletak jauh di luar jalan-jalan aspal. Dibandingkan kota, memang fasilitas di kampung tidak lengkap.
Sanitasi di kampung tidak bagus karena banyak warga membuang hajat dan sampah sembarangan di parit atau got. Dalam musim hujan banyak kampung kebanjiran, meskipun air banjir itu tidak dalam dan kotor. Baru kemudian ketika jumlah penduduk semakin meningkat, air kali sekaligus air banjir menjadi sangat kotor.
Banjir besar mulai melanda Jakarta pada 1932. Banjir itu merupakan siklus 25 tahunan, penyebabnya waktu itu adalah turun hujan sepanjang malam pada 9 Januari. Hampir seluruh kota tergenang. Di Jalan Sabang, sebagai daerah yang nomor satu paling parah, ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Banyak warga tidak bisa keluar rumah, kecuali mereka yang beruntung memiliki perahu (Jakarta Tempo Doeloe, 1989).
Siklus 25 tahunan terulang kembali pada awal Februari 2007 lalu. Memang, kota-kota di negara maju saja sering kali tidak berdaya menghadapi bencana alam. Mudah-mudahan kita mengambil hikmahnya bahwa semakin tertutupnya daerah resapan air, maka banjir semakin besar. Begitu pula semakin buruknya sanitasi.
Sanitasi terburuk umumnya terjadi pada daerah bantaran sungai. Semakin banyaknya pendatang tentu semakin banyaknya permukiman warga sekaligus sampah yang dibuang ke kali. Sudah jelas, perilaku warga yang demikian perlu diubah sehingga banjir yang mungkin terjadi lagi bisa diminimalisasi. (DJULIANTO SUSANTIO)


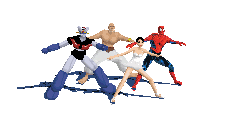


Tidak ada komentar:
Posting Komentar