Gempa besar yang diikuti gelombang tsunami di Aceh dan Nias akhir Desember 2004 lalu, mungkin belum hilang dari ingatan kita. Ketika itu, hampir 200.000 jiwa manusia melayang dan ribuan rumah hancur. Belum termasuk hewan dan harta benda lainnya, seperti perabotan rumah tangga, sawah, kolam, dan buku-buku sekolah.
Memang belum resmi masuk Museum Rekor Indonesia (MURI) atau Guiness Book of World Records, namun bisa jadi suatu saat Aceh dan Nias akan “mejeng”, paling tidak di MURI. Konon dalam tiga abad terakhir, Aceh dan Nias telah dilanda gempa bumi lebih dari 13.000 kali. Suatu jumlah yang relatif besar dibandingkan daerah-daerah lain di seluruh penjuru Indonesia. Meskipun sebagian terbesar berupa gempa kecil, artinya tidak dapat dirasakan oleh manusia tetapi tercatat oleh seismograf, hal itu tetap menunjukkan ke dua wilayah merupakan daerah rawan bencana.
Hingga awal 2007 saja, berbagai gempa bumi masih tetap melanda Aceh dan Nias. Gempa terakhir yang cukup besar terjadi pada pertengahan November 2006 lalu, dengan kekuatan 5,6 Skala Richter.
Bahkan, alam rupanya selalu tidak bersahabat dengan Aceh dan Nias. Kali ini pada akhir Desember 2006 lalu kedua wilayah dilanda bencana banjir bandang. Kloplah rasanya sebutan “Negeri Bencana” diberikan kepada Aceh dan Nias.
Langganan bencana
Kalau kita membuka arsip-arsip lama, tergambar jelas sejak lama Aceh dan Nias merupakan wilayah langganan bencana. Sejumlah dokumen tertulis dari abad XVI hingga XVIII berulang kali menyebutkan Aceh bersama Nias sebagai “Kota Bencana”. Dikatakan, setiap tahun banjir besar, air laut pasang, dan gempa bumi silih-berganti melanda Aceh dan sekitarnya. Karena sering mengalami atau melihat bencana, maka para pedagang dan pengelana asing yang pernah mengunjungi Aceh saat itu, sering menjuluki Aceh sebagai “kota mati” atau “kota yang menyeramkan”.
Yang tercatat agak panjang lebar adalah mengenai bencana banjir pada abad XVII. Sering kali dalam satu kali bencana, sebagaimana tulis Denys Lombard dalam Kerajaan Aceh (Balai Pustaka, hal. 61), menghancurkan satu kampung sekaligus. Meskipun rumah-rumah penduduk dibangun di atas tiang setinggi 1,20 meter hingga 1,80 meter, selalu saja ada sejumlah rumah yang hanyut terseret air.
Rupanya bencana itu demikian besar. Apalagi rumah-rumah di sana sedikit sekali yang terbuat dari batu. Umumnya rumah-rumah penduduk berbahan tumbuhan, seperti alang-alang dan bambu. Dengan demikian tentunya mudah sekali roboh kalau diterjang air besar.
Dilaporkan juga bahwa di sana hampir setiap tahun terjadi banjir akibat pasang purnama dan sungai. Banjir ini sampai menggenangi kota, sehingga orang terpaksa naik perahu dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya untuk mengamankan diri. Tak bisa dibantah, bencana tersebut sudah demikian parah.
Selain itu, masih menurut Kerajaan Aceh, malapetaka kebakaran sering kali menghancurkan berbagai rumah di Aceh. Begitu pun gempa bumi. Malah gempa bumi yang terjadi sebelum matahari terbit pada 7 Maret 1621, kekuatannya begitu besar. Mereka yang berada di dalam rumah merasakan seakan-akan atap rumah roboh menimpa mereka. Sekurangnya setiap tahun terjadi tiga-empat gempa di sana.
Banyaknya bencana di Sumatra, terlebih di Aceh, juga pernah dilaporkan William Marsden dalam bukunya Sejarah Sumatra (1999). Kala itu, menurut Marsden, di Sumatra terdapat sejumlah gunung berapi yang sering mengeluarkan lava sehingga menyebabkan hutan terbakar. Bahkan letusan-letusan gunung berapi itu mempunyai hubungan dengan gempa bumi yang sering terjadi di sana.
Gempa bumi yang paling keras dirasakan sendiri oleh Marsden pada 1770 dan terjadi di daerah Manna. Sebuah kampung dikabarkan musnah. Selain itu banyak rumah runtuh dan habis dimakan api, bahkan beberapa orang tewas. Sebelumnya, pada 1763 Marsden mendapat kabar bahwa seluruh penduduk yang tinggal pada satu kampung meninggal akibat gempa bumi di Nias.
Rupanya gempa yang terjadi pada abad XVIII itu relatif besar karena menurut Marsden, seusai gempa terjadi retakan tanah sepanjang seperempat mil, lebarnya dua depa, dan dalamnya empat atau lima depa. Benda seperti aspal mengalir dari sisi retakan dan tanah. Setelah gempa berlalu, aspal mengerut dan memuai silih berganti. Banyak bagian bukit longsor. Akibatnya Sungai Manna penuh sesak dengan tanah liat. Sering kali gempa diiringi gelombang laut yang dahsyat sehingga goncangannya dirasakan kapal-kapal besar yang membuang jangkar di bandar (hal. 23).
Marsden mengemukakan pula, dibandingkan dengan berbagai kejadian gempa bumi di Amerika Selatan, Karibia, dan negeri-negeri lain, jenis-jenis bangunan di Sumatra lebih tahan gempa sehingga bahayanya bagi penduduk sedikit sekali. Menurut Marsden, biasanya gempa itu terjadi setelah perubahan cuaca, terlebih setelah panas yang menyengat. Sebelumnya didahului bunyi gemuruh sayup-sayup seperti guntur yang jauh. Selain itu gejala gempa ditandai ulah ternak dan unggas peliharaan yang tidak seperti biasanya. Ini karena hewan-hewan itu mampu merasakan getaran abnormal. “Ayam memerlihatkan reaksi seperti yang mereka lakukan bila melihat burung elang,” kata Marsden tentang membaca fenomena alam secara tradisional.
Umumnya rumah-rumah yang didirikan di atas bukit mengalami kerusakan paling parah. Sebaliknya, rumah-rumah yang didirikan di atas pasir dataran rendah paling sedikit merasakan efeknya. Diperkirakan, fondasi dan struktur tanah pasir yang longgar, lebih mampu melawan guncangan dari tanah. “Oleh karena itu gedung-gedung di tanah pasir lebih kebal gempa,” kata Marsden. Setidaknya ini merupakan suatu masukan berharga buat para pakar konstruksi yang akan membangun rumah atau gedung.
Selain gempa bumi, Sumatra khususnya Aceh, sering dilanda surf, yakni alunan ombak tinggi dan pecah di pantai. Tinggi surf mencapai 15-20 kaki (4,5 hingga 6 meter) lalu puncaknya menggantung dan kemudian seluruhnya jatuh seperti air terjun, hampir tegak lurus melebur dirinya. Deru yang diakibatkan oleh hempasan itu sangat keras sehingga dapat terdengar bermil-mil di daratan dalam kesunyian malam.
Gelombang surf mungkin serupa dengan gelombang tsunami. Apalagi, menurut Marsden, tenaga surf sangat kuat. Hal ini terlihat dari sebuah perahu yang terjungkir sehingga puncak tiang layarnya menancap di pasir dan pangkalnya menembus dasar perahu (hal. 25).
Laporan sejenis lainnya, meskipun amat singkat, pernah diberikan sejumlah pengelana Barat. Dikatakan bahwa negeri Aceh tidak terlalu baik dari segi geografis. Bahkan negerinya sering diporakporandakan oleh alam.
Sebenarnya, Aceh merupakan negeri yang cemerlang. Kerajaan Islam Aceh maju pesat berkat perdagangan internasional selama ratusan tahun. Pada zaman penjajahan, Aceh merupakan wilayah di Indonesia yang paling sulit ditaklukkan Belanda.
Mudah-mudahan kemashurannya tidak hilang karena bencana. Justru adanya bencana dapat menjadi model percontohan untuk pengembangan ilmu pergempaan, seperti halnya Jepang yang sering disebut “Negeri Gempa dan Tsunami”. (DJULIANTO SUSANTIO)


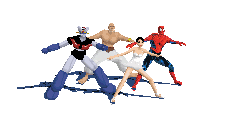


Tidak ada komentar:
Posting Komentar