Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia akhir 2002 lalu, tentu masih segar dalam ingatan kita. Ketika itu lewat pemungutan suara, mayoritas hakim dari Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag (Belanda), menetapkan bahwa Malaysia adalah pemilik sah kedua pulau itu.
Sebenarnya sengketa terhadap kedua pulau itu sudah berlangsung sejak 1970-an. Namun sungguh disayangkan, sikap pemerintah kita waktu itu tenang-tenang saja. Justru Malaysia yang lebih aktif mengincar kedua pulau itu. Bahkan terang-terangan memromosikannya sebagai objek wisata bahari yang menakjubkan milik negerinya. Padahal seharusnya, karena masih dalam keadaan bersengketa, terlebih dulu kedua pulau harus dinyatakan sebagai status quo.
Setiap tahun ratusan ribu wisatawan datang ke sana untuk menikmati taman laut yang dianggap eksotik. Tak ayal, Malaysia banyak mengeruk keuntungan dari objek-objek itu.
Merunut sejarahnya, keberadaan Pulau Sipadan dan Ligitan tak lepas dari masa kolonial yang pernah dialami Indonesia (penjajahan Belanda) dan Malaysia (penjajahan Inggris). Meskipun pemerintah Indonesia memiliki berbagai dokumen sejarah, namun pemerintah Malaysia telah lama memanfaatkan kedua pulau. Justru asas pemanfaatan itu menjadi kunci utama keberhasilan Malaysia dalam memiliki Sipadan dan Ligitan.
Kasus Sipadan dan Ligitan pantas menjadi pelajaran berharga buat kita. Saat ini masih banyak pulau yang rawan sengketa, terutama pulau-pulau terluar, dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Australia, Timor Leste, dan Papua. Kalau tidak hati-hati menanganinya, tidak mustahil sejumlah pulau akan terlepas lagi.
Batas laut, hukum laut internasional, atau zone ekonomi eksklusif saja belum cukup. Perlu ada dukungan dari berbagai disiplin ilmu lain, seperti arkeologi, sejarah, antropologi, dan filologi (naskah kuno).
Metode Arkeologi
Sengketa dua negara atau lebih biasanya berkembang karena adanya pulau-pulau yang dianggap potensial dan secara geografis terletak dekat perbatasan suatu negara. Sejak lama, banyak negara sudah bersengketa dengan tetangganya memerebutkan pulau-pulau potensial. Beberapa persoalan belum terselesaikan hingga kini. Misalnya sengketa Pulau Kuril di Samudra Pasifik antara Jepang dengan Rusia dan sengketa Pulau Falkland (Malvinas) di Samudra Atlantik antara Inggris dengan Argentina. Tak dimungkiri, kurang ada bukti otentik yang menguatkan suatu negara lebih berhak terhadap pulau itu.
Enam negara Asia Tenggara dan Asia Timur kini juga tengah menghadapi sengketa yang tak urung selesai terhadap gugusan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Keenam negara yang tengah memerebutkan pulau kaya minyak, gas, dan hasil perikanan itu adalah China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.
Selama puluhan tahun, banyak pertikaian sering dialami keenam negara itu. Filipina pernah menangkapi kapal-kapal ikan Taiwan karena dianggap telah melanggar kedaulatan perairan mereka. Pasukan China dan Vietnam pernah terlibat pertempuran sengit karena China mencoba menduduki wilayah itu.
Vietnam sendiri bersikukuh merekalah pemilik sah pulau. Ini diperlihatkannya dengan mengirim sekelompok turis untuk pertama kalinya dalam sejarah menuju Pulau Spratly pada April 2004 lalu.
Pemerintah Malaysia juga tidak mau kalah. Mereka membangun fasilitas kepariwisataan di salah satu gugusan kepulauan Spratly. Bahkan semakin digencarkan sejak kemenangannya atas kasus Sipadan-Ligitan dari Indonesia.
China menganggap merekalah yang berdaulat penuh atas Spratly. Argumentasi China adalah mereka yang pertama kali menemukan sekaligus mendudukinya. Fakta itu didasarkan atas berbagai temuan arkeologis di sana.
Sekitar 1991 tim arkeologi China menemukan kapak-kapak batu dan barang keramik. Setelah diidentifikasi, barang-barang kuno itu diketahui berasal dari zaman batu baru (neolitik) dan Dinasti Han (sekitar tahun 200 sebelum Masehi). Benda-benda itu kemungkinan besar dibawa oleh para pedagang China ke Pulau Ganquan, salah satu gugusan kepulauan Spratly itu.
Menurut penelitian selanjutnya, temuan-temuan tersebut mirip dengan artefak-artefak arkeologi sejenis di Pulau Hainan, pulau milik China. Sedangkan dalam dokumen sejarah China diungkapkan bahwa kepulauan itu sudah menjadi milik China sejak 770 SM.
Jelas, metode arkeologi bisa mempetegas status sebuah pulau. Apalagi bila suatu pulau yang disengketakan itu meninggalkan jejak-jejak budaya dari masa silam. Hal ini lebih memudahkan identifikasi, sehingga menentukan negara mana yang berhak atas pulau tersebut. Kecuali bila status sebuah pulau memang sudah jelas, misalnya dari batas garis pantai atau zone laut. Maka penelitian arkeologi dan/atau penelitian lain tidak diperlukan lagi.
Dalam keadaan tidak jelas, penelitian yang bisa dilaksanakan adalah ekskavasi atau penggalian. Ekskavasi biasanya diselenggarakan untuk membuktikan hipotesis. Penelitian lain adalah etnoarkeologi. Para peneliti sebaiknya berasal dari negara-negara yang sedang bertikai itu, ditambah peneliti independen.
Sesungguhnya, turun tangannya arkeologi merupakan cara yang paling ampuh untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan pulau. Ini karena arkeologi berawal dari masa yang jauh ke belakang. Arkeologi pun memiliki sejumlah ilmu bantu yang terdiri atas ilmu-ilmu keras (hard sciences) dan ilmu-ilmu lunak (soft sciences), terutama yang tercakup dalam ilmu-ilmu yang memakai istilah “arkeo” dan “paleo”, seperti arkeoastronomi dan paleobotani.
Pengkajian secara ilmiah oleh kalangan ilmuwan dipastikan lebih bertanggung jawab daripada diselesaikan secara hukum yang undang-undangnya berasal dari warisan masa kolonial. Kalau tidak ada bukti arkeologi, barulah menggunakan cara lain, seperti naskah kuno atau bukti sejarah. (DJULIANTO SUSANTIO)


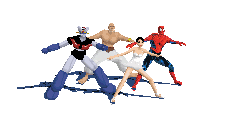


Tidak ada komentar:
Posting Komentar