Pemilu legislatif baru saja usai. Tentu kita masih terkesan dengan kampanye yang mereka lakukan. Poster, baliho, spanduk, iklan media cetak dan elektronik, selebaran, dan cara-cara lain semarak di mana-mana. Namun apakah Anda memperhatikan nama-nama mereka? Sering kali terselip berbagai gelar, seperti MBA, M.Si, M.Hum, Ir, M.M, M.Min, MIA, SE, Drs, lengkap dengan foto masing-masing calon legislatif.
Belum puas menampilkan sederetan gelar akademis, dipajang lagi gelar Dr (HC) atau Doktor “Honoris Causa”. Yang patut dipertanyakan, darimana mereka memperoleh gelar Dr (HC) tersebut? Apakah karena jasa atau prestasinya ataukah boleh membeli?
“Honoris Causa” berasal dari bahasa Latin. Arti sebenarnya, “dengan alasan kehormatan”. Ternyata sesuai kaidah akademis, tidak semua perguruan tinggi dapat menganugerahkan gelar Dr (HC). Hanya perguruan tinggi yang memenuhi syarat yang memiliki hak secara eksplisit untuk memberikan gelar itu.
Syarat utama adalah perguruan tinggi tersebut pernah menghasilkan sarjana dengan gelar ilmiah Doktor dan memiliki fakultas atau jurusan yang membina dan mengembangkan bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan yang menjadi ruang lingkup jasa atau karya bagi pemberian gelar. Selain itu perguruan tinggi tersebut harus memiliki guru besar tetap, sekurang-kurangnya tiga orang dalam bidang sebagaimana dimaksud pada poin di atas.
Singkatnya, perguruan tinggi tersebut harus memiliki ius promovendi atau hak mempromosikan orang menjadi doktor. Jadi, perguruan tinggi yang belum mempunyai program pendidikan pascasarjana tingkat doktor, tidak dapat menganugerahkan gelar Dr (HC).
Sementara itu kriteria bagi penerima gelar adalah memiliki karya atau jasa yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau pendidikan dan pengajaran. Disyaratkan pula, karyanya sangat berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pendidikan dan pengajaran, bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa, dan banyak mengembangkan tenaga serta pikiran bagi perguruan tingginya.
Guru besar
Penentuan siapa-siapa yang berhak memperoleh gelar Dr (HC) juga tidak sembarangan. Terlebih dulu harus dirapatkan oleh senat guru besar. Pemberian gelar kehormatan lazimnya diprakarsai oleh seorang atau sekelompok guru besar dari fakultas yang mengampu bidang ilmu yang bertalian dan kepakaran orang yang dicalonkan sebagai doktor kehormatan. Seorang profesor linguistik, misalnya, menurut Prof. Dr. Anton M. Moeliono dalam sebuah tulisannya di Kompas, tidak pantas mencalonkan seorang dokter meski secara pribadi menjadi teman dekatnya. Jika gagasan itu diterima oleh dewan guru besar fakultas, calon itu kemudian diusulkan kepada rektor universitas/institut.
Rektor kemudian minta pertimbangan tentang usul itu kepada Ketua Dewan Guru Besar (DGB), yang meneruskan usul itu ke komisi DGB yang salah satu tugasnya menilai kelayakan calon penerima gelar itu.
Ketua komisi itu lalu mengundang salah seorang pengusul untuk memaparkan alasan pengusulan itu dalam sidang komisi. Pertimbangan komisi DGB itu disampaikan kepada pimpinan DGB yang menyalurkannya ke senat akademik universitas/institut dan rektor. Selaku pejabat eksekutif tertinggi, rektor mengambil putusan berdasarkan pertimbangan DGB, lalu mengangkat seorang guru besar sebagai promotor atas usul dewan guru besar fakultas yang mengusulkan pencalonan itu. Begitulah langkah-langkahnya.
Wisuda
Hal lain yang perlu diketahui adalah pengukuhan gelar Dr (HC) lazim dilakukan secara individu, bukan secara masal. Menurut tata cara dan tradisi, pengukuhan gelar diberikan oleh rektor. Seusai upacara singkat, maka si penerima gelar membacakan orasi (ilmiah) sesuai bidang keilmuan yang dikuasainya. Misalnya kalau penerima gelar dianggap berjasa di bidang sastra, orasi harus berhubungan dengan bidang sastra, bukan bidang teknik atau lainnya. Begitu pun di bidang-bidang lain, seperti hukum, teknik, tata negara, pertanian, dsb.
Untuk menyemarakkan suasana lazimnya pula pihak perguruan tinggi mengundang pejabat-pejabat penting untuk mengikuti upacara pengukuhan tersebut. Pejabat penting yang dimaksud antara lain presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, dan pejabat pemerintahan lainnya. Selain itu dari kalangan swasta yang mungkin mensponsori kegiatan tersebut.
Sebagai kebanggaan, upacara penganugerahan sering kali diselenggarakan di kampus pemberi gelar, bukan di negara si penerima gelar atau di hotel-hotel berbintang. Syarat lain adalah perguruan tinggi pemberi gelar sudah memiliki akreditasi. Dengan demikian PTS pun boleh memberikan gelar Doktor (HC). Tentu saja dengan memperhatikan tradisi akademik yang ditetapkan.
Pemberian gelar pun tidak terbatas untuk warga negara tertentu, tetapi untuk semua bangsa secara universal. Sebagai contoh, akhir Juli 2007 lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla memperoleh gelar Dr (HC) dalam bidang ekonomi dari Universiti Malaya, salah satu perguruan tinggi bergengsi di Malaysia. Alasan penganugerahan adalah karena JK dianggap berjasa dan memberikan sumbangsih besar untuk memajukan ekonomi global. Pada kesempatan itu Jusuf Kalla menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Arah Ekonomi Indonesia dalam Konteks Regional” di hadapan senat guru besar Universiti Malaya.
Merunut sejarahnya, gelar Dr (HC) tercatat pertama kali diberikan kepada Lionel Woodville pada abad ke-15 oleh Universitas Oxford di Inggris. Pada awalnya pemberian gelar Dr (HC) dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa. Barulah pada abad ke-16 ketika banyak universitas yang belum tenar mendapat kunjungan kehormatan dari Universitas Oxford dan Universitas Cambridge, gelar Dr (HC) mulai memperoleh perhatian.
Doktor “Konyolis Causa”
Tidak dimungkiri, hingga saat ini masih banyak ketidaktahuan dan kejanggalan dalam pemberian gelar Doktor (HC). Selain calon-calon legislatif, tentu masyarakat masih ingat kasus H. Rhoma Irama tahun 2005 lalu.
Ketika itu H. Rhoma Irama terlihat berjalan gagah saat mengenakan toga. Bersama beberapa selebriti lain, dia tengah diwisuda di suatu tempat di Jakarta karena mendapatkan gelar Doktor (HC) dari suatu perguruan tinggi mancanegara yang membuka cabang atau perwakilan di Indonesia. Nama perguruan tinggi tersebut tentu saja masih terasa asing di telinga kita.
Di mata masyarakat awam pastilah tidak ada yang aneh dalam peristiwa tersebut. Namun di kalangan akademisi, timbul tanda tanya besar, Persoalannya adalah penganugerahan gelar Dr (HC) tersebut dilakukan tak ubahnya perayaan wisuda sarjana dan dilakukan secara masal.
Lagi pula H. Rhoma Irama dkk ketika itu tidak menyampaikan orasi. Ketika ditanya oleh pers tentang alasan pemberian gelar Doktor (HC), H. Rhoma Irama mengatakan, “Mungkin saya dianggap berjasa memajukan musik dangdut di tanah air”. Setelah banyak disorot, selebriti lain aktor Anwar Fuady pun mencak-mencak. Tentu saja kepada perguruan tinggi pemberi (baca: penjual) gelar tersebut.
Di luar kedua nama itu, sejak lama memang sudah beredar berbagai orang atau tokoh yang menambahkan gelar Dr (HC) dan gelar akademis lain di depan atau di belakang nama mereka. Fenomena ini mulai marak saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah secara langsung. Di masa kampanye legislatif ini, tidak dimungkiri penyandang gelar demikian semakin bertambah tanpa kita tahu asal-usulnya. Lihat saja berbagai kartu nama yang dibagikan dan poster atau baliho kampanye yang terpasang di setiap sudut jalan.
Tak pelak, penambahan gelar Dr (HC) dan gelar akademis merupakan “nilai tambah” bagi ybs. Dengan nekad, misalnya, pada 2007 seorang calon bupati suatu daerah di Sumatra pernah memajang gelar Dr (HC) sekaligus SSos (Sarjana Ilmu Sosial, pen) untuk kampanyenya. Namun karena diperoleh secara ilegal, dia kemudian dijatuhi hukuman pidana selama lima bulan dengan masa percobaan sepuluh bulan. Kabarnya, gelar-gelar tersebut diperoleh dari Universitas Generasi Muda (UGM) Medan. Yang ironis, keberadaan UGM (mungkin sebagai plesetan Universitas Gadjah Mada) tidak sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi karena sarana dan prasarana yang ada di sana tidak mengindahkan Keputusan Mendiknas dan Dirjen Dikti.
Kemungkinan besar, sang calon bupati itu memperoleh gelar Dr (HC) dengan cara membeli. Sejak lama memang bisnis gelar marak terjadi di Indonesia. Mungkin masih ada yang ingat, pada 1986 Soedomo (mantan menteri) pernah “dianugerahi” gelar Dr (HC). Ternyata setelah ditelusuri, di negaranya (AS) perguruan tinggi tersebut tidak terakreditasi. Selain Soedomo masih ada nama-nama seperti Maya Rumantir (penyanyi pop) dan Iis Dahlia (penyanyi dangdut) yang diberikan gelar tersebut.
Modus baru pemberian (penjualan, pen) gelar Dr (HC) sebenarnya mulai terendus pada 2000 lalu. Ketika itu banyak orang, termasuk penulis, pernah mendapat kiriman surat lewat pos dari Institut Manajemen Global Indonesia. Kemungkinan besar, mereka memilihnya secara acak lewat buku telepon. Dalam basa-basinya dikatakan, “Selamat! Anda terpilih dari sekian banyak warga Indonesia yang berprestasi”.
Ternyata, untuk menyandang gelar Dr (HC) itu penulis diminta “uang partisipasi” minimal Rp 1 juta, sebagai syarat untuk mengikuti upacara wisuda di Istora Senayan Jakarta. Anehnya, kita bisa memilih perguruan tinggi pemberi gelar tersebut yang konon berpusat di Hawaii, AS. Ketika itu ada empat pilihan perguruan tinggi.
Mungkin cara seperti inilah yang dilakukan para calon pemimpin daerah dan calon anggota legislatif 2009. Mereka tidak sungkan-sungkan memasang sederet gelar karena di negara kita gelar akademis masih dianggap sakral sebagai lambang status dan lambang feodalisme. Kalau ada sejumlah calon yang memasang gelar demikian, kita anggap saja gelar Doktor “Konyolis Causa”. Artinya, manusia konyol yang masih memuja gelar demi keuntungan pribadi. Kecuali tentunya kalau gelar Doktor (HC) tersebut benar-benar diraih berkat prestasi yang luar biasa. (DJULIANTO SUSANTIO)


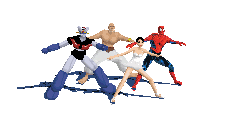


bagus...bagus..bagus... setuju banget tuch dengan Doktor Konyolis Causa-nya...
BalasHapus